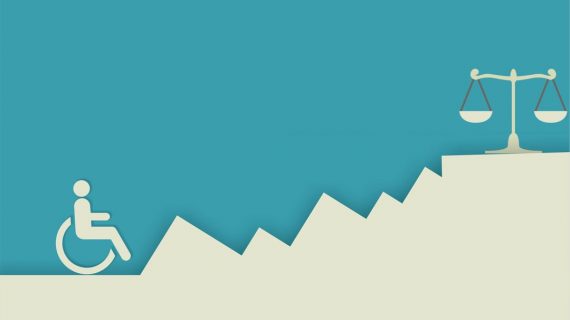Apakah menikah dengan difabel bisa dianggap sebagai tidak sekufu atau tidak memenuhi syarat kafaah?
Jumhur ulama’ berpandangan bahwa yang wajib memenuhi standar kafa’ah (sekufu) adalah laki-laki, bukan perempuan. Tujuannya, agar masing-masing pihak tidak merasa terhina di mata keluarga besar atau masyarakat. Lalu apakah menikah dengan difabel termasuk kafa’ah?
Memang melalui kafa’ah lah, sepasang suami istri akan memperoleh ketenangan, kebahagiaan, dan ketentraman. Tidak akan ada bentuk penghinaan atau diskriminasi yang akan terjadi di dalam keluarga karena merasa ada ketidaksepadanan dalam berbagai sisi.
Lalu apakah bentuk kebahagiaan itu dapat diperoleh melalui pertimbangan fisik, materi, atau agama. Tentang hal ini, ulama’ sesungguhnya sepakat bahwa agama lah yang didudukkan pada posisi pertama. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang aspek sekunder apa saja yang digunakan sebagai standar kafa’ah setelah agama.
Hanafiyyah menetapkan enam aspek; agama, keIslaman, merdeka, nasab, kekayaan (harta benda), dan pekerjaan. Sementara Malikiyyah hanya menetapkan dua aspek; agama dan terbebasnya seseorang dari disabilitas. Syafi’iyyah mentapakan lima hal, yaitu agama atau ‘iffah (kualitas keberagamaan), merdeka, nasab, terbebas dari disabilitas, dan pekerjaan. Hanabilah menetapkan lima hal yang berbeda dari rumusan Syafi’iah, yaitu agama, merdeka, nasab, kekayaan, dan pekerjaan.
Maka, hanya ada dua kelompok ulama’; Malikiyyah dan Syafi’iyyah, yang mengaitkan disabilitas (‘aib/cacat) dengan kafa’ah. Sementara yang lainnya tidak.
Kondisi disabilitas yang dirumuskan pun hanya berkaitan dengan disabilitas fisik dan mental. Jumlahnya ada sembilan di mana jenis disabilitas fisik lah yang mendominasi. Hanya satu yang berakaitan dengan mental, yaitu junun: penyakit gila atau terganggung ingatannya. Selebihnya berkaitan dengan disabilitas fisik.
Namun, jika dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, tiga di antaranya dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan, yaitu junun (penyakit gila), juzam (lepra/kusta), baras (penyakit belang). Sementara dua jenis yang lain hanya terjadi pada laki-laki saja, yaitu; jub (terpotongnya kemaluan) dan ‘unnah (impoten).
Sisanya hanya dapat ditemui pada perempuan, yaitu: qarn (daging di dalam kemaluan yang menghalangi jima’), ratq (tersumbatnya kemaluan), fatq (sobeknya bagian antara qubul dan dubur), dan afl (daging di dalam kemaluan atau bau tidak sedap dari kemaluan yang menganggu hubungan seksual).
Beberapa kondisi disabilitas di atas menurut ulama’ Malikiyyah dan Syafi’iyyah tidak berlaku mutlak untuk dianggap tidak kafa’ah. Pihak laki-laki maupun perempuan dapat memilih atau menetapkan untuk melanjutkan atau menghentikan rencana perkawinan.
Di sini para ulama’ tidak mengaitkan beberapa kondisi disabilitas lainnya yang umumnya terjadi. Jenis disabilitas sensorik; seperti disabilitas netra, rungu, dan wicara, dan intelektual terlihat tidak didudukkan sebagai standar kafa’ah. Ini memberikan penekanan pemahaman yang sangat krusial. Artinya, menikah dengan difabel, baik orang yang disabilitas netra, rungu, dan wicara tidak dianggap tidak sekufu.
Kondisi disabilitas yang telah dirumuskan oleh ulama’ sebagai pertimbangan dalam kafa’ah memiliki resiko yang cukup besar dalam pernikahan dapat dibenarkan. Entah itu akan berpengaruh pada masalah reproduksi atau penyakit. Ulama’ terlihat memiliki pertimbangan yang matang untuk menghindari terjadinya kerugian dalam pekawinan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atas terlaksananya perkawinan.
Hal ini adalah salah satu bentuk penerapan asas etika perkawinan; yaitu prinsip otonomi. Prinsip ini berakaitan dengan kehendak seseorang untuk memilih seorang pasangan sehingga tidak terjadi penyesalan di kemudian hari.
Apapun itu pertimbangannya, yang jelas disabilitas fisik yang dirumuskan ulama’ itu saat ini mesti dapat teratasi dengan baik. Dunia medis yang semakin canggih mampu memberikan solusi atas disabilitas yang di alami oleh seseorang. Karena itu, mestinya tidak ada lagi pandangan yang terkesan mendiskriminasi pasangan hanya karena masalah sekunder atau bahkan tersier.
Konsep utama kafa’ah; yaitu agama, yang disepakati jumhur ulama’ justru seakan telah menghilangkan perdebatan kaitan disabilitas dalam kafa’ah. Memprioritaskan keagamaan atau agama, pandangan yang terkesan memarginalkan kelompok disabilitas akan tertutup seketika. Bahwa derajat kegamaan dan intelektualitas keagamaan yang diutamakan adalah keniscayaan yang tidak dapat ditawar dalam merealisasikan tujuan kehidupan yang hakiki.
Ketika diskusi ini diarahkan pada hukum Islam positif, perbedaan mencolok terlihat jelas. Kompilasi Hukum Islam (KHI) jelas tidak menghadirkan ragam perbedaan sebagaimana fikih. KHI hanya akan menetapkan beberapa item saja atau satu item yang disepakati sebagai standar kafa’ah. Ini tidak lain sebagai konsekuensi langkah positivisasi hukum Islam.
Atas dasar itu, konsep kafa’ah yang ditetapkan dalam KHI terlihat jauh lebih progressif dari apa yang dirumuskan dalam fikih. Pasal 61 menegaskan bahwa:
“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama”.
Dengan meletakkan aspek keagamaan yang hanya digunakan sebagai standar kafa’ah, maka secara otomatis item-item standar kafa’ah lainnya yang tersebar di fikih tidak lagi dipandang relevan untuk menentukan keberlangsungan pernikahan.
Langkah ini memberikan dampak pemaknaan yang lebih fundamental, terutama untuk penyandang disabilitas. Sisi fisik dan materi-kondisi belum bekerja misalnya- tidak lagi menjadi masalah bagi peyandang disabilitas yang seringnya memperoleh pre-understanding yang buruk karena keterbatasan kemampuannya.
Langkah KHI dalam memangkas segala persyaratan kafa’ah yang dianggap dapat menimbulkan banyak perselisihan dan gesekan sosial ini sejatinya telah mengajarkan bagaimana agama menjadi landasan dalam membangun rumah tangga. Agama lah yang akan menjadi pedoman dan menuntun suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sedangkan aspek-aspek yang lain hanyalah pemandu sekunder yang boleh untuk tidak diikuti.
Salah satu fungsi perkawinan dalam konteks ini tampakya juga memiliki korelasi erat dengan mengapa agama atau keberagamaan berada di posisi pertama dalam kafa’ah. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perkwinan memiliki fungsi keagamaan; melestarikan risalah kenabian (agama). Ini hanya dapat diperoleh jika pertimbangan agama diutamakan.
Keyakinan teguh orangtua terhadap Islam memiliki andil besar dalam mengkonstruksi pendidikan dan agama anak turunnya. Sampai-sampai Rasulullah menegaskan;“Semua anak terlahirkan dengan membawa (potensi) fitrah keagamaan yang benar. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia menganut agama Yahudi, Nasarani, atau Majusi”.
Sekali lagi, ini adalah bukti bahwa Rasulullah benar-benar menganjurkan aspek keagamaan seseorang sebagai prioritas kafa’ah. Bukan aspek lain yang hanya akan menghasilkan perdebatan dan dapat berujung pada penghormatan atau penghinaan kemanusiaan. Itu hanya akan menghasilkan gesekan sosial dan bahkan kemungkinan terburuknya dapat merusak hubungan haromonis kekerabatan atau kekeluaragaan yang telah terbangun. (AN)
Wallahu A’lam
_____________________
Ditulis oleh Mukhammad Nur Hadi – Alumnus Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta